Ada beberapa kejadian yang begitu membekas buat saya sampai sekarang. Tidak banyak yang tahu – karena mungkin selama ini orang hanya tahu kalau saya menang penghargaan A, B, C, atau tampil di X, Y, Z, atau bikin Ruangguru sampai jadi seperti sekarang. Saya pun jarang membahas ini karena saya pikir, “Udah lah, ini cerita lama. Saya juga udah move on, dan tidak penting juga mengumbar cerita sedih.”
Tapi saya gemas sekali melihat fenomena di dunia maya kita, dan saya tidak lagi ingin nonton – dan hanya bisa bilang, “Kasihan ya, dia habis di-bully sama haters-nya.”
Peristiwa 1
Tahun 2003. Waktu itu saya masih kelas 5 SD. Salah seorang teman menertawakan dengan memanggil saya ‘bencong kampung’. Awalnya saya tidak menggubris, karena ini toh juga bukan kali pertama saya dipanggil seperti itu.
Penyebabnya sederhana, simply karena waktu SD saya lebih banyak menghabiskan waktu bermain dengan teman-teman perempuan. Saya juga tidak suka ikut bermain bola atau main PlayStation. Intinya hobi saya waktu itu cenderung ke stereotipe anak baik-baik seperti membaca buku, ikut lomba, dan sebagainya.
Tapi kali itu berbeda, teman saya tidak puas kalau saya hanya diam saja. Jadi dia melanjutkan aksinya dengan turut menghina orangtua saya juga.
Singkat cerita, saya ikut terpancing. Saat itu saya yang tengah berada di lapangan, segera mengambil batu – yang ukurannya cukup besar, dan melemparkan ke kepalanya hingga jatuh dan bersimbah darah. Untungnya dia bisa diselamatkan waktu itu. Momen serupa juga pernah terjadi sekitar setahun sebelumnya, ketika saya diejek dengan hal yang sama dan berakhir dengan ‘tonjokan’ menggunakan Tipp-Ex ke mukanya hingga berdarah. Untung saja tidak sampai kena matanya.
Apa yang saya lakukan di peristiwa pertama ini jauuuh sekali dari stereotipe anak pintar yang biasanya disematkan ke saya.
Mana ada juara kelas bisa mengamuk sampai temperamental begitu. But hey, that was happened.
Kita tidak tahu tombolnya orang itu di mana, dan ketika kita pencet tombolnya, trigger-nya ternyata pas!
Butuh waktu bertahun-tahun untuk saya melatih temperamental dan bisa lebih sabar menghadapi sesuatu, terutama untuk tidak terpancing ketika menghadapi cemoohan orang. Saya mencoba untuk belajar mengalihkan amarah saya ke hal-hal yang lebih positif – gue berusaha membuktikan diri dengan prestasi.
Peristiwa 2
Tahun 2004. Saya maju menjadi kandidat ketua OSIS di SMP dan salah satu persyaratannya adalah harus melakukan kampanye di depan seluruh siswa. Ketika giliran saya berdiri di atas podium, saya masih ingat ada seseorang yang melempar sampah makanan di saat saya menyampaikan pidato.
Banyak yang melihat kejadian itu dan saya pun tahu segerombolan anak yang melakukannya tertawa senang melihat saya dipermalukan seperti itu. Saya berusaha untuk tetap terlihat tegar, tapi setelah turun panggung saya berlari ke toilet dan menangis di sana. Saya merasa bahwa saya tidak disenangi orang dan tidak akan ada yang memilih saya.
Saya tahu persis dan percaya diri bahwa secara kualitas saya adalah kandidat terbaik saat itu – tapi orang tidak suka dengan saya dan saya bukan cuma malu tapi bingung tidak bisa berbuat apa-apa, karena bahkan saya tidak tahu kenapa orang tidak suka.
Nobody told me why – what I knew, they just hated me. Dan benar, ketika hasil pemungutan suara diumumkan nama saya berada di urutan terakhir dengan perolehan hanya 40 suara.
Peristiwa kedua ini menimbulkan luka mendalam. Rasa percaya diri seketika runtuh, setidaknya untuk terlibat dalam hal-hal yang sifatnya komunal. Saya akhirnya takut untuk memimpin apa pun karena saya tahu meskipun ada skill-nya tapi saya merasa tidak akan pernah bisa mengatasi satu problemanya yakni ‘kenapa orang membenci saya’.
Beruntung akhirnya saya masih bisa mengalihkan fokus untuk berprestasi dan tampil secara individu – dan lebih banyak berkarya di luar sekolah. Bagi saya saat itu, luar sekolah adalah lingkungan yang lebih aman. Baru pada akhirnya saat SMA saya menemukan seorang mentor yang amat berjasa dalam hidup yang membantu saya kembali untuk menumbuhkan rasa percaya diri dan penerimaan diri.
Saya tidak mau playing victim berlebihan. Saya tidak membenarkan bagaimana saya bereaksi terhadap kedua peristiwa tersebut. Semestinya saya bisa merespon dengan cara yang lebih baik. Tapi mungkin wawasan saya dulu baru sampai di situ sehingga itulah reaksi spontannya.
Seiring bertambahnya usia dan semakin bertumbuh dewasa, self-awareness dan empati saya juga makin terasah. Saya jadi jauh lebih sensitif untuk mengidentifikasi masalah dan melakukan refleksi pada diri sendiri. Saya juga jadi paham bahwa saya juga punya salah. Kadang, I probably hated my old self dan kadang saya berpikir, “Pantas saja ya dulu orang kesal sekali sama saya.”
Kedua cerita ini jarang sekali saya sampaikan ke publik. Bukan apa-apa, tapi saya sebenarnya orang yang tidak terlalu suka untuk membicarakan masa lalu apalagi menjual kisah sedih seperti ini untuk mendapat belas kasih. No way. Bukan itu tujuan saya berbagi kisah ini. Di balik segala prestasi atau capaian yang sudah diraih sejauh ini (yang mungkin hanya itu yang orang tahu tentang saya), ada banyak hal lainnya yang juga saya lalui dengan cara yang tidak mudah. Really, it was not easy at all. Saya beruntung bisa keluar dari ‘lubang’ ini – thanks to support system yang luar biasa yang saya miliki.
Tapi saya tahu, tidak semua orang seberuntung saya yang bisa keluar dari masalahnya sendiri. Saya tidak mau ada anak-anak lain yang mengalami hal serupa seperti apa yang saya alami. Tapi sayangnya yang saya lihat justru sebaliknya…
It doesn’t get better, it gets worse.
Terutama dengan perkembangan media sosial saat ini. Kita bisa bersembunyi di balik anonimitas dan bereskpresi semau kita. Yang dihadapi saat ini bukan hanya satu orang teman seperti yang menghina saya dulu itu, tapi warganet yang bisa beramai-ramai jadi ‘orang suci’, bergerombol, dan memaki sesuka hati. Yang dihadapi saat ini, adalah tuntutan untuk conform dengan tuntutan sosial yang makin sulit untuk dicapai. Yang dihadapi saat ini bukan hanya gosip a la anak SMP yang beredar dari satu teman ke teman lain, tapi dalam satu hari seseorang bisa jadi ‘pahlawan nasional’ atau justru ‘public enemy nasional’.
Dari kedua peristiwa di atas, momen-momen tersebut masih membekas sekali dalam diri saya. Mungkin kini saya sudah ratusan kali tampil di depan umum, mulai dari yang hanya ditonton ratusan orang hingga bicara di stadion dengan ribuan penonton atau bahkan disaksikan jutaan orang.
Tapi kadang saya masih merasa takut. Saya masih trauma, takut bahwa orang mungkin akan tidak suka dengan apa yang saya sampaikan, atau takut bahwa saya akan bicara hal yang semestinya tidak disampaikan. Saya masih suka terbayang bagaimana jadinya kalau tiba-tiba orang walk out, bagaimana kalau kejadian saat SMP dulu terjadi kembali.
Saya masih takut.
Mungkin orang yang melempar sampah dulu juga sudah lupa kalau dia pernah sejahat itu kepada saya. Mungkin juga sebenarnya orang yang menertawakan saya tidak pernah benar-benar berniat mengejek – mungkin dia pikir itu cuma main-main dan lucu-lucuan saja. Hanya saja apesnya, saya yang jadi objek penderita. Tapi kejadian-kejadian itu meninggalkan bekas yang dalam.
Sama halnya seperti komentar-komentar kita di media sosial. Mungkin kita berpikir bahwa komentar kita hanyalah lelucon. Mungkin kita berpikir, "Ah, paling komentar saya juga tidak akan terbaca oleh dia." Atau kita berpikir, "Ah, memang sudah sepantasnya dia dihina secara massal." Kita tidak pernah tahu apa yang dihadapi orang lain. Kita tidak pernah tahu cerita lengkapnya – apakah orang ini cuma mengurus 'masalah ini semata' ataukah dia punya 'masalah-masalah lain'. Kita tidak tahu apakah komentar-komentar kita akan meninggalkan luka dan apakah luka itu membekas dan apakah bekas itu bisa cepat diobati atau tidak.
We don't know...
Saya sedih sekali – sangat sedih, melihat betapa judgmental-nya kita (bahkan ke anak-anak yang masih dalam proses perkembangan). Terlebih saat mengetahui mereka sampai berpikir untuk mengakhiri hidup dengan bunuh diri hanya karena tidak mampu lagi menghadapi tekanan sosial yang sudah jauh kelewat batas.
Kadang kita berpikir, "Ah, ini saya nasehatin supaya dia berubah. Supaya nanti tidak mengulangi lagi." Tapi kita lupa, untuk membuat seseorang berubah ada tahapan-tahapan yang perlu dilalui. Tidak setiap orang bisa menerima 'makanan' apa saja dan mengunyahnya dengan cara yang sama.
Ini bukan cerita inspiratif. Ini bukan tentang saya, atau merujuk pada siapa pun. Ini hanya salah satu cara saya mengekspresikan keresahan – dan saya berharap ada yang cukup peduli untuk sama-sama belajar menjadi bijaksana.
Saya paham bahwa setiap tindakan ada konsekuensi. Kita punya hukum yang berupaya mengatur dan melindungi. Haruskah kita ikut-ikutan jadi polisi? Haruskah kita ikut-ikutan menghakimi? Haruskah penghakiman kita diketahui orang? Di mana empati kita? Apakah kita tidak punya ruang lagi untuk memaafkan?
Who have we became?
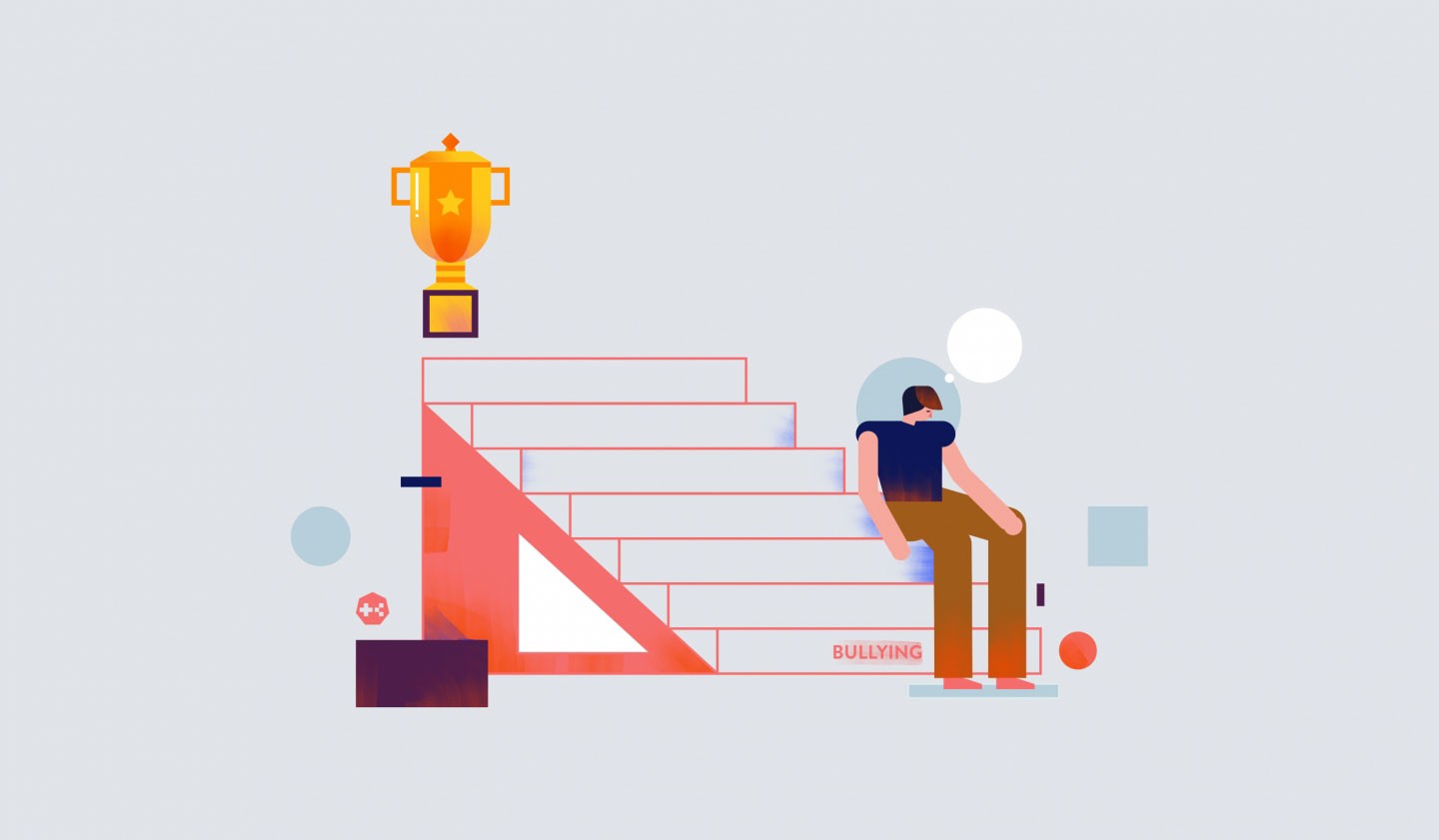


 By Greatmind x BeautyFest Asia 2024
By Greatmind x BeautyFest Asia 2024

 By Idgitaf
By Idgitaf

 By Atya Faudina
By Atya Faudina