Indonesia tengah terus berbenah, termasuk kota-kotanya. Kita dapat melihat dari banyaknya percepatan pembangunan infrastruktur di sejumlah kota sebagai respon dan antisipasi dari pemenuhan kebutuhan hidup penduduk sekaligus peningkatan standar pelayanan kota. Ya, setiap kota memang tidak bisa berhenti untuk terus berkembang. Namun di setiap upaya perkembangannya, apakah kita telah merencanakannya dengan seksama berlandaskan pemahaman komprehensif, kontekstual serta mengantisipasi tuntutan keberlanjutan masa depan dengan cerdas dan realistis?
Pembangunan infrastruktur kota itu secara keruangan atau spasial sebagian besar bersifat irreversible. Kesalahan penempatan, pemilihan jenis, kesalahan konstruksi, kegagalan pemenuhan standar operasi dan sejenisnya tidak dapat diperbaiki atau diulangi dalam waktu singkat, karena usia infrastruktur dikondisikan mencapai puluhan tahun. Bahkan struktur melayang dan terowongan bawah tanah bisa mencapai 70 hingga 100 tahun. Sekali salah tempat, maka infrastruktur tersebut menempati ruang publik layaknya zombie.
Isu besar lain yang kita hadapi saat ini adalah bagaimana kita dapat mengelola kepadatan ruang kota seefisien mungkin namun menghasilkan produktivitas dan kemaslahatan publik sebesar mungkin. Kita selalu meyakini nenek moyang kita adalah seorang pelaut. Bila memang demikian adanya, maka kita seyogyanya adalah masyarakat yang memiliki pola pikir maritim dalam garis besar pengambilan keputusan untuk bertahan hidup. Hidup di pesisir memberi kesadaran jika lahan adalah aset terbatas sementara wilayah perairan laut nyaris menawarkan yang tidak terbatas karena akan selalu ada sesuatu di balik horison. Penduduk maritim menyadari bahwa sumber daya terbesar ada di luar sana, bukan di dalam sini. Oleh karenanya mereka banyak mengembangkan layar, mengangkat sauh, dan melintasi samudera untuk melakukan tukar menukar dan perdagangan dalam mencukupi kebutuhan mereka. Penuh tantangan, penuh risiko, namun terdapat reward yang menanti. Sementara sumber daya yang mereka miliki di wilayah sendiri, pada hakikatnya terbatas dan harus dapat dikelola sedemikian rupa agar dapat dipergunakan untuk jangka waktu selama mungkin. Semua bangsa besar adalah bangsa dengan pola pikir maritim.
Berseberangan dengan pola pikir maritim adalah pola pikir kontinental. Pola pikir ini dimiliki oleh mereka yang tinggal di pedalaman, dengan segala kecukupan sumber daya mengelilinginya. Tanah yang subur, hasil bumi yang melimpah, serta air bersih yang mudah didapat. Secara praktis, cenderung berpikir seolah tidak ada batas ketersediaan sumber daya, karena mereka tidak ‘melihat’ batasnya. Sumber daya tersebut seolah-olah tidak pernah habis hingga membuat masyarakat pedalaman ini tidak menyadarinya. Secara umum, boros sumber daya adalah ciri yang nampak pada diri masyarakat dengan pola pikir pedalaman.
Pola pikir maritim di Nusantara ini memang pernah mengemuka yaitu setidaknya saat kejayaan Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, yang berorientasi ke laut (sea going) dengan menaklukan banyak tempat, dan menjadi bagian dari pergaulan dunia dalam kegiatan perdagangannya. Namun singkat cerita saat bangsa Eropa mulai menginjakkan kaki di tanah air dan banyak menguasai wilayah pesisir serta ditambah simpul kekuasaan kerajaan lokal banyak yang bergeser ke pedalaman, maka penduduk lokal lebih terdorong mengembangkan budaya feodalisme daripada budaya persaingan perdagangan. Semenjak era kolonialisme, menurut hemat saya, bangsa kita lebih ditempa untuk memiliki pola pikir defensif daripada progresif. Yaitu lebih terfokus pada eksplorasi dan eksploitasi sumber daya yang ada, daripada mendapatkan nilai tambah dari sumberdaya eksternal. Adalah suatu ironi besar ketika negara kita yang tergolong negara kepulauan terbesar di dunia, namun ternyata masyarakatnya cenderung memiliki mental kontinental daripada maritim.
Sebagai negara kepulauan, seharusnya kita sangat menyadari keterbatasan sumber daya lahan yang ada. Namun ternyata, semenjak kemerdekaan, perkembangan luas area pembangunan di kota dan desa seperti tak terbendung. Perluasan wilayah urban seiring dengan peningkatan populasi dan kekuatan ekonomi menjadi kota berskala mega luput dipahami sebagai suatu kemunduran. Sebagai ilustrasi, saat ini Jakarta memiliki luas sekitar 670 kilometer persegi. Sebagai pembanding, di tahun 2006, Singapura memiliki luas yang sama dengan Jakarta ini. Bedanya, Singapura adalah negara kota pulau yang dikelilingi air, sementara Jakarta masih memiliki area daratan pendukung yang seolah berlimpah. Mari kita simak perbedaan pola pikir yang melandasi tata kelola ruang antar dua kota berbeda yang kurang lebih memiliki luas yang sama tersebut.
Singapura sadar betul bila wilayah kota mereka dikelilingi oleh air, oleh karenanya dalam pola pikir mereka tertanam bagaimana mereka harus dapat mengelola tata ruang di wilayahnya sedemikian rupa agar dapat difungsikan seoptimal mungkin baik secara komersial maupun secara ekologis untuk jangka waktu yang berkelanjutan. Sementara dari evolusi tata ruang Jakarta, dari sejak merdeka hingga kini sulit dikatakan bahwa pengelola kota telah berpikir dengan pola pikir yang berkelanjutan tersebut. Rasio wilayah pemukiman di Singapura hanya mengambil 12% saja dari total luas areanya terutama karena sebagian besar hunian dibangun secara vertikal. Sisa lahannya sebanyak 19% difungsikan untuk taman kota, 13% sebagai jalan raya, serta 30% lebih untuk fungsi militer, fungsi ekologis dan tabungan lahan pembangunan masa depan. Sementara itu, wilayah pemukiman di Jakarta mengambil area sebesar 65 % total luas wilayahnya, dengan hanya menyisakan taman kota sebanyak 2% dan hanya 6% untuk jalan raya. Tidak ada definisi lahan yang ditabung untuk masa depan.
Secara praktis, karena kurangnya ruang terbuka publik, maka streetscape atau ruang jalan di Jakarta yang hanya sekitar 6% tersebut juga berfungsi sebagai public space untuk warganya. Semua warga menggunakan area jalan untuk berkegiatan. Mulai dari rute moda transportasi umum, jalan bagi kendaraan pribadi, lapak pedagang di beberapa tempat, hingga tempat berolahraga bagi siapa saja dalam sejumlah kesempatan. Bayangkan jika sebagian besar streetscape Jakarta tersebut kelak akan dipenuhi oleh berbagai struktur melayang yang saling tumpang tindih dan menutupi ‘ruang publik praktis’ penduduk Jakarta tersebut. Kota Jakarta akan kehilangan langit dan cakrawala, sinar matahari semakin berkurang, sementara polusi suara dan udara semakin mencekam.
Di lain pihak, dengan meluasnya kota (urban sprawl) secara kurang terkendali serta meroketnya harga tanah akibat spekulasi harga lahan yang begitu bebas menyebabkan kelas menengah kota termarjinalkan ke pinggiran bahkan ke luar kota. Apa yang tinggal di dalam kota adalah penduduk kelas bawah yang memang tidak mampu menjauh dari ruang kota serta penduduk kelas atas yang memang sanggup tinggal dengan standar dan biaya hidup tinggi di dalam kota. Persinggungan diametral antara kelas bawah dan kelas atas penduduk kota ini menajamkan segregasi sosial sistemik yang ditandai dengan semakin tingginya kecemburuan sosial kelas bawah sementara di lain pihak, kelas atas menderita paranoia sosial yang antara lain mengakibatkan maraknya pemukiman tertutup berpagar (gated communities).
Fenomena peningkatan harga tanah spekulatif tersebut, nyaris tidak ada korelasinya dengan peningkatan mutu dan kapasitas sarana dan prasarana kota seperti jalan raya, taman kota ataupun sarana transportasi publik. Generasi milenial pun semakin terancam tidak akan mampu membeli tanah dan rumah di lokasi yang masuk akal untuk dihuni. Sesungguhnya apa yang dialami kota semacam Jakarta ini adalah suatu kebencanaan yang bersifat kronis, cukup dirasakan namun tidak cukup untuk menggerakkan upaya mitigasi bencananya. Ciri-ciri kebencanaan kronis adalah tidak semua orang sepakat untuk menyatakan peristiwa yang mendegradasi mutu kehidupan tersebut sebagai suatu kebencanaan. Lihatlah Pemerintah Amerika di bawah Presiden Trump yang tanpa sungkan menyangkal adanya fenomena global warming.
Tanah atau lahan adalah sumber daya yang harus dimanfaatkan seefisien mungkin dan secara efektif harus dapat memberi nilai tambah setinggi-tingginya secara berkelanjutan sehingga generasi mendatang masih dapat menikmatinya sebagaimana halnya kita menikmatinya saat ini. Inilah pola pikir sustainable development yang menurut saya selaras dengan pola pikir maritim dalam hal kemampuan menyadari keterbatasan sumber daya internalnya.
Berbicara mengenai keberlanjutan, saya merangkum secara mendasar ke dalam tiga prinsip pengelolaan sumber daya. Yaitu efisiensi sumber daya, konservasi sumber daya, dan berbagi sumber daya. Konservasi sumber daya, sering dikemukakan namun cukup sulit diaplikasikan, yaitu berupa penggunaan teknologi energi terbarukan. Prinsip yang lebih mudah dilakukan adalah efisiensi sumber daya dan prinsip berbagi sumber daya karena keduanya menyangkut pengendalian tabiat dan perilaku manusianya sendiri.
Membangun hunian secara vertikal, membuka peluang ruang terbuka lebih untuk area publik, mengkoneksikannya dengan pembangunan angkutan massal yang aman, nyaman dan andal merupakan salah satu penerapan prinsip berbagi sumber daya. Berbagi sumber daya serta berbagi fasilitas memungkinkan keberlangsungan ekosistem lingkungan dan sosial suatu kota yang lebih baik dan berimbang. Apalagi jika dipadukan dengan kebijakan pengendalian harga tanah, maka hal ini pun akan memungkinkan kelas menengah kembali menghuni kota dan meredam kecenderungan segregasi sosial.
Sesungguhnya semangat dan perilaku berbagi sumber daya sudah mulai dipahami dan dilakukan generasi milenial. Lihatlah disrupsi atas model bisnis konvensional telah melahirkan banyak fenomena berbagi sumber daya: co-working space, carpool yang melahirkan kendaraan on-demand atau daring, Airbnb, dan sebagainya. Perluasan penerapan prinsip berbagi sumber daya ini ke sektor lain, terutama pada domain publik seperti perumahan vertikal yang baik dan transportasi umum yang andal sangat dimungkinkan. Namun tentunya, pemerintah pun harus mengubah paradigma penataan dan pengelolaan sumber daya seperti lebih berani menomorsatukan barang publik daripada barang privat. Alih-alih mensubsidi BBM yang hanya mendorong kepemilikan mobil pribadi di kelas menengah, seharusnya pemerintah lebih mendorong subsidi transportasi massal, insentif perumahan kelas menengah, pengendalian tata ruang dan tata guna lahan yang lebih terpadu dengan jaringan transportasi publik melalui perencanaan yang lebih seksama dan mendetail, mereduksi spekulasi kenaikan harga tanah yang tidak masuk akal, serta lain sebagainya. Memang bukan hal mudah mengubah suatu paradigma berkehidupan. Diperlukan dukungan, kolaborasi, dan perjuangan banyak pihak untuk mewujudkan semua ini – menanam sebanyak mungkin agen perubah baik di tubuh pemerintah, masyarakat, pemain swasta dan industri, serta keluarga kita masing-masing.
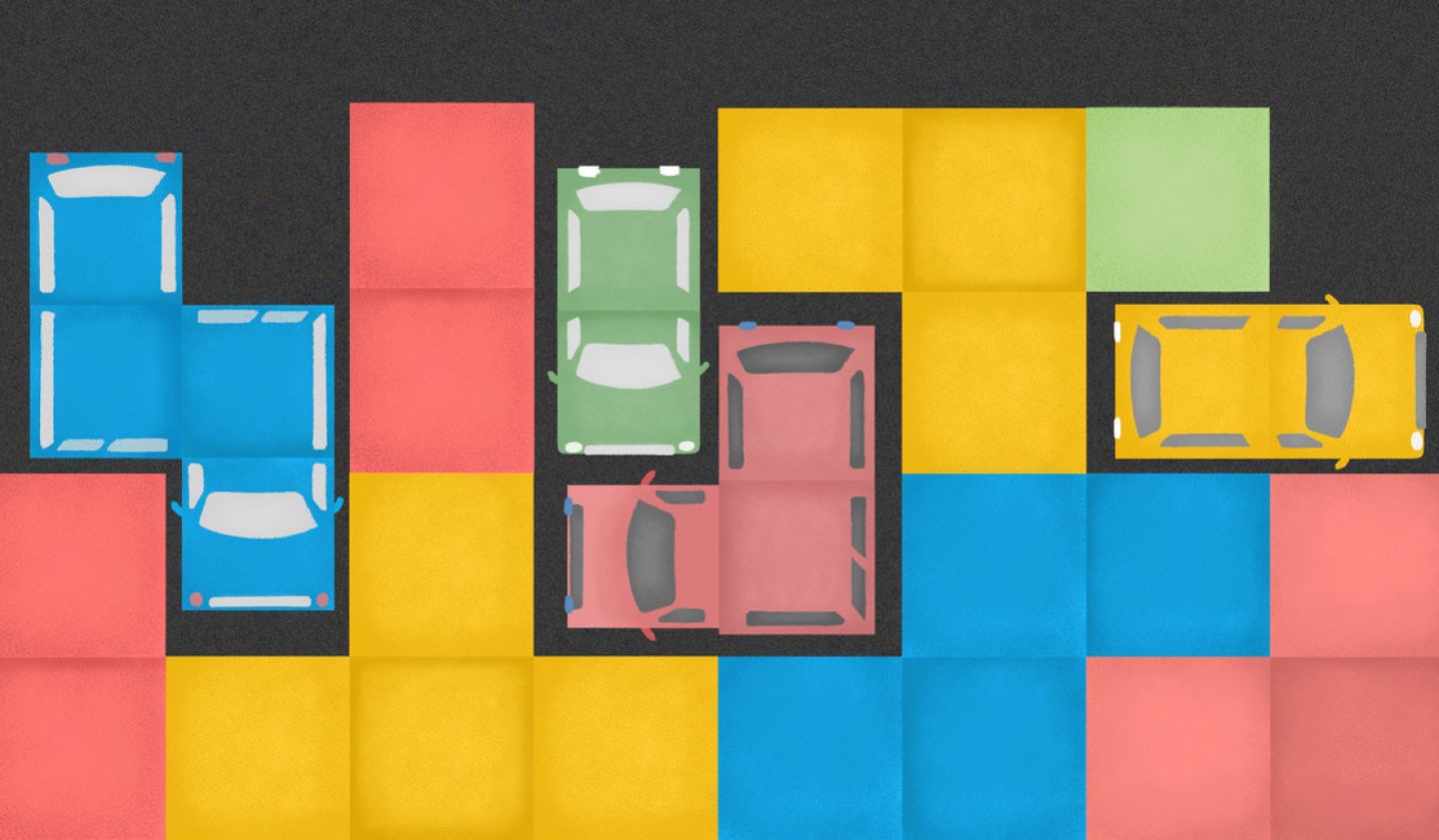


 By Hendrick Tanuwidjaja
By Hendrick Tanuwidjaja

 By Abigail Limuria
By Abigail Limuria

 By Ari Sutanti
By Ari Sutanti